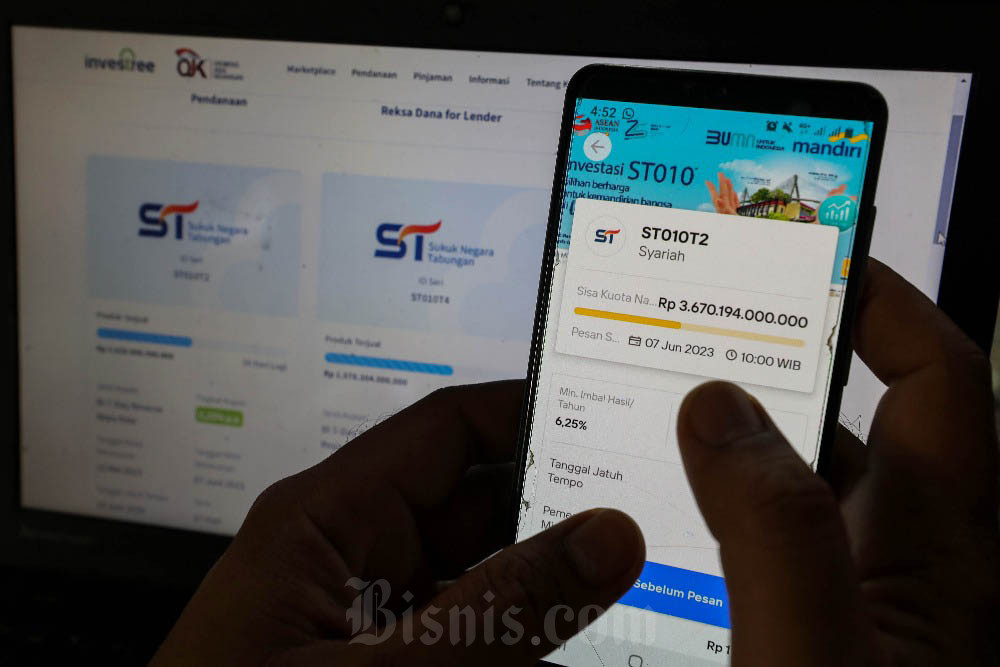Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi likuiditas industri perbankan di Tanah Air masih menjadi polemik. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) melihat kelonggaran likuiditas. Longgarnya ruang likuiditas tercermin dalam pemenuhan kewajiban penyangga likuiditas makroprudensial (PLM).
Ketentuan rasio PLM 5% surat berharga negara (SBN) yang ditetapkan BI bagi bank umum sudah dapat dipenuhi oleh mayoritas perbankan. Bahkan, beberapa bank tertentu mampu melampaui jauh di atasnya.
Di sisi lain, sejumlah bankir justru mengungkapkan sebaliknya. Likuiditas mengetat lantaran perebutan likuiditas di pasar uang. Persaingan memburu likuiditas tidak hanya terjadi antarbank, tetapi juga dengan lembaga keuangan nonbank.
Penyusutan kepemilikan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) seakan menjadi bukti valid. Nilai SRBI Rp 526,17 triliun yang dipegang perbankan per Maret 2025 adalah yang terkecil dalam sembilan bulan terakhir. Artinya, bank harus ‘mencairkan’ SRBI guna memenuhi kebutuhan likuiditasnya.
Sampai di situ, rasio PLM, kepemilikan SRBI, dan likuiditas perbankan seakan ‘berbicara’ sendiri-sendiri tanpa ‘dialog’ dalam satu jalinan cerita utuh yang terbingkai dengan isu penyaluran kredit. Bagaimanapun bank adalah salah satu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi finansial.
Fungsi intermediasi menjembatani antara pihak berlebih dana dengan pihak butuh dana. Pihak berlebih dana bisa langsung meminjamkan dana mereka kepada pihak butuh dana. Tingginya kebutuhan dana niscaya tidak akan terpenuhi dari transaksi langsung secara individual.
Baca Juga
Kehadiran bank juga mengemban fungsi transformasi maturitas. Simpanan nasabah pada umumnya dalam jumlah kecil dan bertenor pendek. Sementara, debitur perbankan membutuhkan pinjaman dana dalam jumlah besar dan dengan masa pengembalian jangka panjang.
Alhasil, indikator perbankan yang menghubungkan antara sisi hulu dan sisi hilir tampaknya lebih relevan. Parameter berskala lebih mikro bisa dipakai untuk menengahi polemik likuiditas. Rasio antara pinjaman dengan simpanan (loan to deposit ratio/LDR) secara industri toh masih di bawah 90%.
Besaran LDR tersebut menunjukkan dana pihak ketiga yang dihimpun industri perbankan belum optimal tersalur untuk pembiayaan. Pertumbuhan kredit di Maret 2025 pun ‘hanya’ 9,16% secara tahunan, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kinerja itu juga menjadi yang terlambat dalam 16 bulan terakhir.
Perspektif waktu juga perlu dirujuk untuk memahami secara utuh problema likuiditas. Pada periode tertentu penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit akan menaik dan pada periode lainnya akan menurun, serta berbalik naik lagi pada level sebelumnya. Perilaku semacam itu cenderung berulang.
Alhasil, likuiditas perbankan sejatinya bersifat temporer alih-alih permanen. Kelebihan likuiditas ditempatkan perbankan pada SBN yang dapat digunakan sebagai back stop liquidity. Secara simetris, bank berhati-hati dalam penyaluran kredit, kendati likuiditas mencukupi dan ruang untuk ekspansi kredit tetap terbuka luas.
Ketidakcermatan dalam menyelami fenomena roller coaster semacam itu membawa implikasi yang tidak ringan pada kebijakan turunannya. Likuiditas menentukan suku bunga. Suku bunga akan naik jika likuiditas mengetat. Dalam kasus likuiditas ‘bias’ ke atas, kebijakan suku bunga acuan bisa keliru arah.
Likuiditas juga bertautan dengan giro wajib minimum (GWM). Pemangkasan GWM yang mengacu pada likuiditas yang terlalu tinggi sangat boleh jadi memperparah sebaran likuiditas. Bank besar dengan sumber daya signifikan kian leluasa. Sementara itu, bank kecil dan menengah tetap saja kesulitan dalam penghimpunan dana.
Bagaimanapun, suku bunga acuan adalah kebijakan yang berlaku seragam untuk semua bank. Demikian pula, GWM tidak secara spesifik menunjuk pada satu bank tertentu, alias ‘gelondongan’ yang mencakup semua bank tanpa memilah detail subjeknya. Jelasnya, rasio GWM tidak bisa disamaratakan untuk semua bank.
Dengan argumen divergensi itu, BI perlu selektif. Pelonggaran GWM bisa diposisikan sebagai peranti strategis agar bank mampu meningkatkan penyaluran kredit pada sektor-sektor tertentu. Sektor padat karya, hilirisasi, pariwisata, UMKM, ekonomi hijau, dan ekonomi biru layak memperoleh prioritas pemangkasan GWM.
Sebagai imbangannya, perbankan sendiri juga harus inovatif dalam menyikapi setiap kebijakan yang diberlakukan. Alih-alih ‘cengeng’ meminta dispensasi khusus, perbankan perlu meracik ulang komposisi portofolio optimalnya dalam mengemban amanah intermediasi dan transformasi maturitas.
Sejalan dengan itu, perbankan semestinya memiliki cadangan mandiri untuk mengantisipasi siklus akselerasi pertumbuhan kredit. Demikian pula, perbankan juga perlu menyiapkan sumber dana murah sebagai alternatif di luar dana pihak ketiga yang selama ini menjadi andalan.
Dengan skenario dua sisi tersebut, roller coaster likuiditas hanyalah ‘riak-riak’ kecil dalam ‘lautan’ perbankan yang tenang. Pada akhirnya, ketangguhan postur industri perbankan akan berkontribusi nyata pada stabilitas sistem keuangan dalam rangka keberlanjutan pertumbuhan inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Bukan begitu?